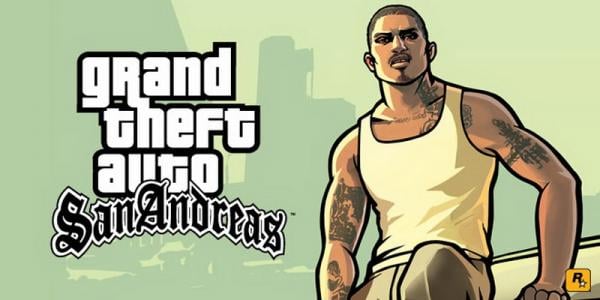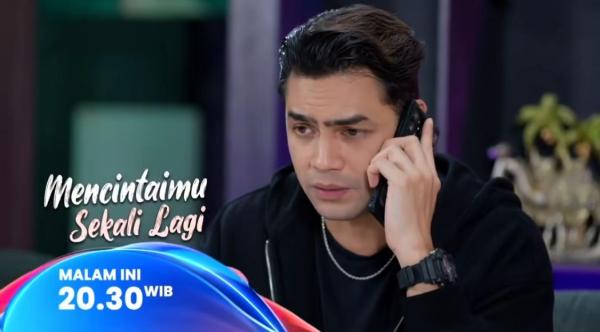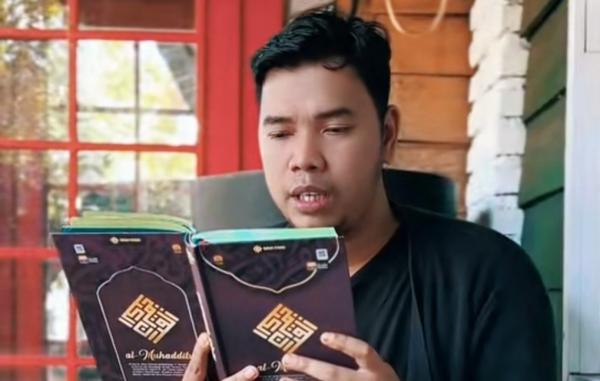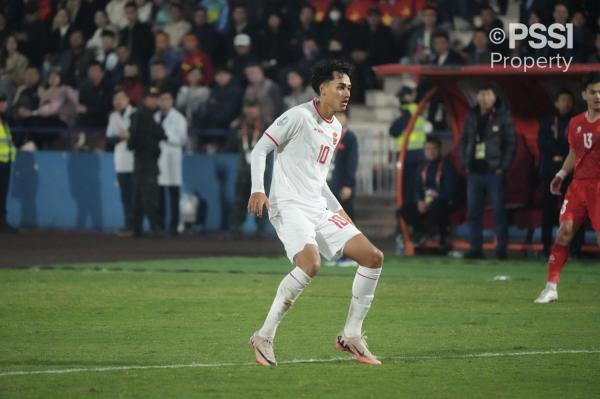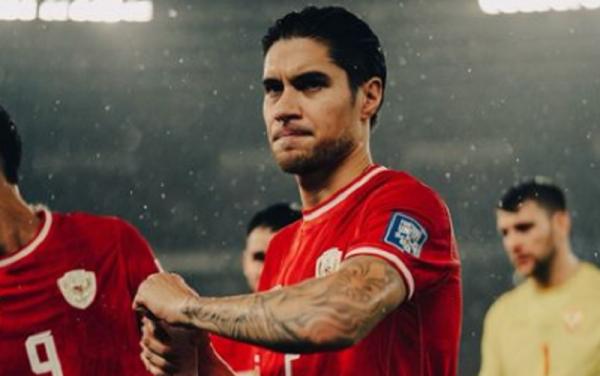Harryanto Aryodiguno, Ph.D
Associate Professor, International Relations Study Program, President University
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang tatanan perdagangan internasional dengan kebijakan tarif barunya. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan baru-baru ini, Trump mengumumkan penerapan tarif impor sebesar 10 persen untuk produk umum, dan hingga 54 persen bagi negara-negara yang dianggap memiliki hambatan perdagangan besar. China menjadi target utama dengan tarif tertinggi, sementara negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos juga turut terkena imbas dengan tarif antara 46 hingga 49 persen.

Baca Juga
Siapa Abdullah Al Sabah? PM Kuwait yang Sempat Dituduh Masuk Kristen
Langkah ini dengan cepat memicu perhatian internasional. Banyak pengamat menilai kebijakan ini bukan sekadar tindakan ekonomi, melainkan bagian dari strategi geopolitik yang ditujukan untuk membendung pengaruh China serta memukul rantai pasok alternatif di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, Indonesia mungkin tampak "selamat" karena tidak disebut secara langsung. Namun, satu gejala penting perlu disoroti, kekosongan posisi duta besar AS untuk Indonesia yang hingga kini belum terisi.
Bagi dunia diplomasi, ketidakhadiran seorang dubes bukan sekadar urusan administratif, melainkan sinyal kuat tentang prioritas hubungan bilateral. Dari perspektif realisme dalam hubungan internasional, ketertarikan strategis AS terhadap Indonesia kini tidak berada dalam daftar teratas, terutama jika dibandingkan dengan fokus Washington pada isu Laut China Selatan, Taiwan, dan hubungan dengan sekutu utama seperti Jepang dan Filipina. Indonesia tampaknya tidak cukup "mendesak" bagi Washington untuk segera menempatkan figur penting di Jakarta.
Namun, hal ini bukan sepenuhnya salah pihak AS. Diplomasi Indonesia pun belum menunjukkan upaya signifikan untuk meningkatkan bobot hubungan ini. Padahal, Indonesia bisa dan seharusnya menyuarakan pentingnya kehadiran seorang dubes melalui berbagai kanal, baik jalur diplomatik resmi, pertemuan bilateral, hingga forum multilateral seperti Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Diamnya Indonesia justru bisa dimaknai sebagai tanda bahwa hubungan ini tidak menjadi prioritas dari sisi kita sendiri.
Dalam konteks perdagangan, sikap pasif ini juga terlihat. Sejumlah komoditas strategis Indonesia seperti karet, tekstil, dan kelapa sawit (CPO) masih menghadapi tantangan besar di pasar AS. Namun, belum ada lobi aktif yang dilakukan untuk meraih pengecualian tarif atau penundaan sanksi ekonomi. Negara-negara lain bahkan mampu memanfaatkan seminar, suara dari think-tank, akademisi, hingga diaspora untuk menekan dan memengaruhi opini publik serta elite di Washington. Indonesia, sebaliknya, masih bertumpu pada diplomasi formal dan administratif yang kerap kali lamban dan tidak strategis.
Kita belum berhasil membangun narasi yang meyakinkan bahwa stabilitas dan kemakmuran Indonesia juga penting bagi kepentingan strategis Amerika Serikat. Padahal, dalam konteks Indo-Pasifik, Indonesia punya posisi geografis dan demografis yang sangat strategis—jembatan antara Samudra Hindia dan Pasifik, negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, serta pasar dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Semua ini adalah kekuatan potensial yang selama ini belum sepenuhnya dioptimalkan dalam diplomasi.
Di sinilah titik kritisnya. Diplomasi Indonesia selama ini terlalu administratif, belum menjadi kekuatan strategis nasional. Diplomasi kita belum menjelma sebagai orkestrasi menyeluruh dari kekuatan bangsa. Pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademik, media, dan diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara belum bergerak serentak membentuk ekosistem diplomatik yang solid. Kita sering kali menunggu arahan atau reaksi, alih-alih memimpin dengan gagasan dan inisiatif.
Kegagalan mengamankan posisi dalam kebijakan tarif AS, serta ketidakhadiran figur Duta Besar AS di Jakarta, seharusnya menjadi pelajaran penting. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan birokratis dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah. Indonesia perlu menyusun ulang pendekatan diplomatiknya dengan Amerika Serikat: dari yang bersifat pasif menjadi proaktif, dari administratif menjadi strategis, dan dari terfragmentasi menjadi terkoordinasi secara nasional.
Dengan potensi besar yang kita miliki, Indonesia seharusnya bisa tampil bukan sekadar sebagai mitra yang hadir, tetapi sebagai mitra yang penting yang mampu menunjukkan nilai tambah bagi stabilitas kawasan dan kepentingan strategis negara mitra seperti Amerika Serikat. Inilah saatnya diplomasi Indonesia naik kelas.
Editor: Maria Christina

 11 hours ago
7
11 hours ago
7